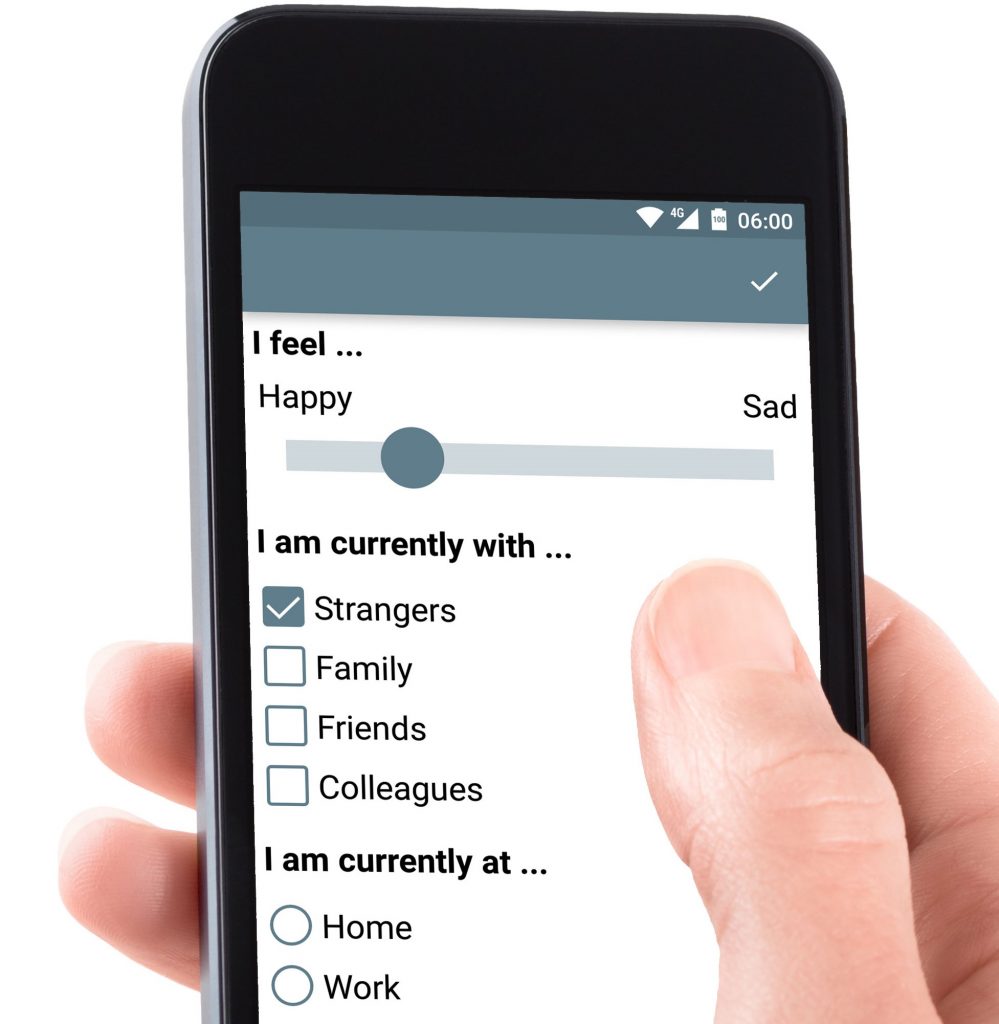Oleh: Anindito Aditomo | Pertama terbit 19 Mei 2014 di MEDIA INDONESIA
PEKAN lalu seorang pelajar SMA dari Surabaya menulis sebuah surat
terbuka untuk M Nuh, menteri pendidikan dan kebudayaan. Surat itu berisi
kritik yang tajam, dengan logika yang baik, tetapi dalam bahasa yang
santun. Substansi kritik surat tersebut sudah cukup banyak dibahas dan
tidak akan saya ulang di sini. Yang saya soroti dalam tulisan ini ialah
jawaban M Nuh ketika ditanya wartawan tentang surat tersebut. Alih-alih
memberi apresiasi, ia justru tidak percaya bahwa seorang pelajar SMA
bisa menulis surat seperti itu.
Respons M Nuh tentu mengecewakan, tetapi tidak mengejutkan.
Ketidakpercayaan Pak Menteri sudah bisa diduga karena konsisten dengan
arah kebijakan mendasar yang dipilih kementeriannya. Yang pertama ialah
penguatan fungsi ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa SMP dan
SMA. Yang kedua ialah penggantian kurikulum tingkat satuan pendidikan
dengan kurikulum 2013. Kedua kebijakan itu pada dasarnya mencerminkan
ketidakpercayaan akut terhadap kapasitas profesional guru sebagai ujung
tombak pendidikan. Bila terhadap guru saja M Nuh sangsi, apalagi pada
siswa-siswanya?
Profesionalitas tanpa otonomi
Secara resmi, pemerintah telah mengakui guru sebagai profesional. Hal
itu berarti kerja guru diakui sebagai aktivitas yang padat pengetahuan
(knowledge-intensive), yang memerlukan keahlian khusus yang diperoleh
melalui rangkaian pengalaman belajar sistematis dan ekstensif. Salah
satu implikasinya ialah bahwa guru, sebagaimana dokter dan akuntan,
seyogianya dipercaya untuk bekerja secara otonom/ mandiri berdasarkan
professional judgment mereka.
Kewenangan untuk bekerja secara otonom itu sesuai dengan kerangka
kualifikasi nasional yang ditetapkan pemerintah (PP No 8 Tahun 2012).
Dalam kerangka itu, kompetensi seorang profesional mencakup kemampuan
merencanakan dan mengelola sumber daya dalam lingkup tanggung jawabnya,
serta mengevaluasi secara komprehensif hasil kerjanya. Secara finansial,
pengakuan profesionalitas guru juga tecermin pada pemberian tunjangan
profesional bagi yang telah lulus sertifikasi.
Yang menjadi masalah ialah pengakuan formal dan penghargaan finansial
tersebut tidak diikuti dengan pemberian kepercayaan (trust). Justru
sebaliknya, pemerintah mengebiri kewenangan guru dalam melaksanakan
aktivitas profesionalnya. Salah satu aspek kunci aktivitas mengajar
ialah melakukan assessment hasil belajar siswa. Namun, melalui kebijakan
ujian nasional pada SMP dan SMA (serta ujian daerah untuk tingkat SD),
pemerintah pada dasarnya mengatakan guru tidak bisa dipercaya melakukan
evaluasi hasil belajar siswanya sendiri.
Sebaliknya, evaluasi pembelajaran hanya bisa dilakukan tim pakar dari
pusat, melalui ujian yang isinya dijadikan rahasia negara. Paket soal
pun dibuat sampai 20 jenis, untuk memastikan siswa (dan para gurunya)
tidak bisa saling menyontek. Bahkan ada daerah yang sampai menyadap
telepon seluler para guru agar mereka tidak membocorkan soal ujian.
Pesan yang disampaikan implisit, tapi gamblang: pemerintah tidak
percaya bahwa guru bisa mampu merancang soal ujian yang baik, atau dapat
menilai muridnya sendiri dengan objektif. Ini ibarat pemerintah,
melalui Departemen (Kementerian) Kesehatan, ngotot menguji hasil
diagnosis dan pengobatan setiap orang yang mendapat pelayanan dari
dokter di Indonesia. Tentu itu pemikiran yang absurd. Namun, itulah yang
terjadi pada di dunia pendidikan.
Namun, bukan hanya itu. Pemerintah juga mencabut kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) yang belum genap 10 tahun diterapkan. Salah
satu landasan filosofis KTSP ialah yang mengetahui konteks dan kebutuhan
bela jar siswa ialah guru dan sekolah. Dengan demikian, sekolah diberi
kewe nangan untuk menyusun kuri kulumnya sendiri, dengan mengacu ke
beberapa capaian belajar nasional. Guru juga harus membuat rencana ajar
(lesson plan) mereka sendiri. Tentu itu menuntut keahlian profesional
tersendiri.
Otonomi itu dicabut dengan berlakunya kurikulum 2013. Sekolah tidak
lagi boleh menyusun kurikulumnya sendiri. Guru pun diminta untuk sekadar
melaksanakan lesson plan yang telah disiapkan tim dari pusat. Bahkan
buku ajar dan materi lain juga dipasok. Materi dan proses pengajaran
dari Aceh sampai Papua, untuk kota megapolitan Jakarta sampai desa
pelosok terpencil, diharapkan sama. Guru pun berhenti menjadi
profesional dan beralih menjadi tukang penyampai informasi.
Mencari presiden yang pro-guru
Apakah keadaan ini menunjang proses pembelajaran? Apakah dalam
keadaan seperti ini, guru dapat mengajar dengan inovatif? Apakah siswa
menjadi bersemangat untuk belajar dan haus pengetahuan? Tak dimungkiri,
ada sebagian guru yang lebih senang dengan pengebirian otonomi
profesionalnya. Apalagi disertai dengan reward finansial berupa
tunjangan profesi yang relatif besar bagi mereka.
Namun, untuk sebagian besar yang lain, uang saja tidak akan
menumbuhkan keinginan intrinsik untuk menjadi kreatif dan inovatif.
Sebuah teori psikologi klasik mengatakan uang hanyalah faktor yang
mencegah seseorang untuk berhenti kerja. Uang tidak dapat membuat
seseorang menyenangi dan mau mencurahkan segenap jiwa untuk
pekerjaannya. Untuk itu, ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang mesti
dipenuhi, seperti otonomi dan kompetensi. Kebutuhan akan otonomi
terpenuhi ketika seseorang diberi kepercayaan dan kesempatan untuk
berpikir dan kemudian bertindak mandiri. Kebutuhan kompetensi terpenuhi
ketika pekerjaan seseorang memungkinkannya untuk terus tumbuh, menguasai
pengetahuan dan keterampilan baru.
Momentum pemilu tahun ini membuka harapan bahwa presiden baru akan
terbuka untuk melakukan reformasi mendasar di bidang pendidikan. Apa
yang harus dilakukan? Solusi jangka pendeknya sebenarnya amat jelas.
Pertama, hentikan penggunaan ujian nasional sebagai komponen penentu
kelulusan siswa dan kembalikan wewenang evaluasi kepada guru dan
sekolah. Itu sejalan dengan Pasal 58 UU No 20/2003 yang menyatakan
evaluasi hasil belajar siswa dilakukan pendidik, serta Pasal 61 yang
menegaskan ujian diselenggarakan satuan pendidikan.
Kedua, cabut kurikulum 2013, dan kembali berlakukan KTSP. Ini juga
sejalan dengan UU No 20/2003 Pasal 36 sampai 38, yang menjelaskan bahwa
pengembangan kurikulum dilakukan satuan pendidikan berdasarkan prinsip
`diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan
peserta didik’. Kurikulum yang seluruh perangkat pendukungnya dibuat
secara terpusat jelas melanggar prinsip itu. Kedua kebijakan korektif
itu ialah langkah awal yang memungkinkan guru untuk mengajar secara
lebih bermakna, bukan sekadar untuk menuntaskan materi dan mengejar
nilai ujian.
Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah harus serius
meningkatkan kualitas guru serta menutup kesenjangan antardaerah. Hal
itu dimulai dengan reformasi lembaga pendidikan guru dan sistem
pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk guru yang sudah mengajar.
Sediakan bank soal untuk topik-topik penting, latih para guru untuk
merakit tes yang diperlukan, kemudian percayakan pada mereka untuk
mengevaluasi muridnya. Tanpa kepercayaan kepada guru, sampai kapan pun
pendidikan kita akan jalan di tempat, atau bahkan mundur teratur.